 Jakarta Indonesia-Rasio utang Indonesia terhadap Gross Domestic Product (GDP) saat ini mencapai 27 persen (GDP sekitar Rp 13.000 triliun). Dengan rasio tersebut, setiap penduduk Indonesia memiliki tanggungan utang negara sebesar US$ 997 atau setara Rp 13 juta perkepala.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jika dihitung dari hampir 260 juta penduduk, diperkirakan perkepala dari kita semua memiliki utang masing-masing US$ 997. Diakuinya angka tersebut masih cuku tinggi, tapi tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.
Mantan Direktur pelaksana World Bank ini membandingkan rasio utang negara lain yang masih jauh lebih besar dibandingan Indonesia. Dikatakannya, Di Amerika Serikat, setiap kepala menanggung utang US$ 62.000. Sedangkan di Jepang bahkan mencapai sebesar US$ 85.000.
"Saat ini rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 30% dan defisit APBN pada kisaran 2,5%. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya," jelas Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Facebook-nya, Jumat (7/7).
Ia memastikan, Indonesia tetap mengelola utang secara prudent (hati-hati). Presiden Joko Widodo tengah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur di Indonesia. “Ini merupakan upaya pemerintah mengejar ketinggalan pembangunan," lanjutnya.
Pemerintah sejauh ini memang menilai utang menjadi sesuatu yang tak bisa terelakan mengingat Indonesia masih mengalami defisit anggaran beberapa tahun terakhir. Misalnya saja, penerimaan dalam APBN P 2016 diproyeksikan sebesar Rp 1.786,2 triliun dengan belanja negara Rp 2.082,9 triliun.
Namun, penerimaan hanya terealisasi Rp 1.551,8 triliun (86,9 persen dari target) dengan realisasi belanja negara Rp 1.859,5 triliun (89,3 persen dari target). Defisit anggaran pun tercatat Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen terhadap PDB.
Di dalam APBN 2017 penerimaan negara di proyeksikan sebesar Rp 1.750,3 triliun, dengan rencana belanja sebesar Rp 2.080,5 triliun. Defisit anggaran pun dipasang di angka 2,41 persen terhadap PDB atau Rp 330,2 triliun.
Angka-angka ini kembali diubah lewat APBN Perubahan 2017 mengingat ada asumsi target penerimaan pajak masih akan mengalami shortfall tahun ini. Artinya, utang bakal menjadi jalan cepat buat pemerintah untuk menambal kurangnya penerimaan negara.
Dalam rancangan APBN-P 2017, shorfall penerimaan perpajakan ditaksir mencapai sekitar Rp 48 triliun. Konsekuensinya, target perpajakan pun direvisi turun dari Rp 1.499 triliun menjadi Rp 1.451 triliun. Sayangnya, shortfall pajak justru tidak diikuti oleh pemangkasan belanja, seperti yang dilakukan pada tahun 2016 lalu. Alasan pemerintah, saat ini tengah butuh biaya besar untuk mengenjot infrastruktur.
Pada APBN-P 2017, pagu belanja negara justru dinaikkan dari Rp 2.080,5 triliun menjadi Rp 2.111,4 triliun. Alhasil, defisit anggaran akan naik dari Rp 330,2 triliun menjadi Rp 397 triliun. Ujungnya defisit membengkak dari 2,41% menjadi 2,92 terhadap PDB, hampir menyentuh batas atas defisit anggaran 3 persen dari PDB sesuai UU Keuangan Negara.
Dengan kenaikan defisit tersebut, total utang pemerintah yang akan ditarik meningkat dari Rp 384,69 triliun menjadi Rp 426,99 triliun. Jika anggaran utang tersebut terealisasi, maka pada akhir 2017, outstanding utang pemerintah akan mencapai Rp 3.962,86 triliun.
Sebuah ‘percepatan’ pertumbuhan utang yang signifikan. Bisa dilihat total utang baru selama 2,5 tahun terakhir sudah mencapai Rp 1.210,92 triliun. Sebagai perbandingan, dalam tiga tahun terakhir pemerintahan sebelumnya (SBY), tambahan utang baru ‘hanya’ mencapai Rp 619,74 triliun.
Bahkan, pertumbuhan utang dalam 2,5 tahun pemerintahan Joko Widodo saat ini, masih lebih besar dibandingkan penambahan utang pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY secara keseluruhan lima tahun (2009-2014) yang sebesar Rp1.019 triliun. Sampai akhir tahun ini, hampir dipastikan utang pemerintahan Joko Widodo pun akan bertambah dan melampaui level Rp 1.500-an triliun dalam tiga tahun pertamanya. .
Defisit Keseimbangan Primer
Pertanyaannya, apa yang menjadi parameter negara harus belanja lebih besar di banding pendapatannya yang diproyeksikan selama setahun ke depan? Mengapa setiap tahun belanja negara harus meningkat, sementara pertumbuhan pendapatan terus tak bisa mengejar pertumbuhan kebutuhan belanja?
Jika besaran belanja negara ini tahun depan sama seperti tahun ini, apakah harus dianggap negara tak berkembang? Faktanya, untuk memenuhi hasrat belanja negara, utang yang ditarik pemerintah lewat sejumlah instrumen dan kreditur jumlahnya sudah sangat besar dan makin sulit dikurangi.
Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, saldo utang pemerintah selalu meningkat. Jika di tahun 2012, posisi utang pemerintah sebesar Rp 1.977,77 triliun, di tahun 2016 menjadi sebesar Rp 3.511,16 triliun.
Hingga Mei 2017 posisi utang pemerintah pusat mencapai Rp 3,672,43 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp2,943,72 triliun atau 80,16 persen dari total utang. Sementara sisanya, Rp 728,7 triliun merupakan pinjaman.
Sejak awal penyusunan anggaran di tahun sebelumnya, pemerintah memang sudah menetapkan kekurangan (defisit) bakal ditutup oleh utang. Rencana penarikan utang pun sudah disusun sesitematis mungkin dengan jadwal yang terencana.
Bahkan strategi berutang pun disusun hingga ada istilah Front Loading Strategy atau menarik utang di awal periode tahun berjalan. “Selama anggaran direncanakan selalu defisit, maka pasti ada penambahan utang,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Menurut mantan Menteri Keuangan ini, utang menjadi kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang masih melambat. Dijelaskannya, dari sisi konsumsi rumah tangga dan investasi swasta cenderung melambat, sehingga diperlukan dorongan belanja pemerintah yang lebih ekspansif.
Defisit budget sejatinya diterapkan untuk mengganti skema budget berimbang (pengeluaran tak boleh lebih dari pendapatan) yang sebelumnya digunakan dalam APBN pemerintahan Orde Baru. Namun, kini skema ini diubah, APBN boleh defisit asalkan dalam batas yang wajar. Sehingga ditetapkan batas maksimal defisitnya sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Mantan Wakil Presiden Boediono, sebetulnya memang tidak ada penjelasan ilmiah mengenai batasan tersebut hal itu. "Saya membuat kebijakan itu hanya menyontek dari Eropa," ujar Menteri Keuangan periode 2001-2004 tersebut dalam sebuah diskusi di Kementerian Keuangan beberapa tahun lalu.
Kala itu, cara tersebut dinilai jitu untuk menjawab masalah saat itu; utang membengkak, penerimaan minim, sementara itu Indonesia butuh tenaga untuk menggenjot perekonomian yang saat itu masih minus 13 persen. Hanya saja, ternyata skema defisit budget tersebut masih terus dilakukan sampai saat ini.
Ekonom INDEF Enny Sri Hartati kepada Validnews mengatakan, ketika defisit APBN melebar itu artinya pemerintah butuh uang yang biasanya diambil lewat jalan utang. Menurutnya, utang memang bukanlah barang haram, hanya saja harus dilihat lagi seberapa efektif utang tersebut digunakan untuk memacu penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.
“Masalahnya, utang ini punya garansi nggak untuk meningkatkan penerimaan pemerintah ke depan? Ini ditunjukkan dari neraca keseimbangan primer,” kata Enny.
Sayangnya, sejak 2012 terjadi defisit keseimbangan primer hingga tahun depan terus bertambah. Ini menunjukkan belanja APBN tidak efektif. “Jadi kita ambil utang, tapi beban kita bertambah, malah menambah defisit. Buat apa kita ambil utang kalau akhirnya hanya untuk menutup utang lama, bukan untuk kegiatan produktif,” lanjutnya.
Sekadar mengingatkan, Neraca Keseimbangan Primer adalah realisasi pendapatan negara dikurangi dengan realisasi belanja negara, di luar pembayaran utang. Defisit keseimbangan primer menunjukkan adanya utang yang digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo pada tahun tersebut, ibaratnya gali lubang tutup lubang.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Keuangan terlihat pada 2011, nilai keseimbangan primer pada APBN masih positif sebesar Rp 8,9 triliun (realisasi). Kemudian berubah negatif menjadi Rp -52,8 triliun (2012), Rp -98,6 triliun (2013), Rp -93,3 triliun (2014), Rp -142,5 triliun (2015), Rp-125,6 (2016), Rp -109 Triliun (APBN 2017) dan Rp 178 triliun (APBN Perubahan 2017).
Dengan keseimbangan primer yang terus negatif tersebut, dapat dikatakan kemampuan APBN kita untuk mengurangi beban utangnya masih lemah. Kondisi ini perlu segera diperbaiki agar tidak membahayakan kesehatan fiskal,
Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri sempat mengakui, postur APBN belakangan ini memang tidak sehat. Karenanya, pengelolaan APBN harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menjadi momok bagi APBN itu sendiri.
"Kalau ingin belanja lebih banyak, harus mendapatkan pajak yang lebih banyak. Dengan demikian seluruh kebutuhan bisa didapat dan tidak membahayakan ekonomi," kata Sri Mulyani dikutip dari Antara (12/7).
Mengenai penetapan target APBN, khususnya anggaran belanja, Sri bahkan menilainya sebagai sesuatu yang cukup lucu. Jika pada satu sisi, pemerintah harus menetapkan anggaran belanja yang pasti akan digunakan, di sisi lain pemerintah harus menetapkan penerimaan yang tak pasti akan diperoleh.
Ironisnya, utang yang sudah disiplin ditarik sesuai jadwalnya, selalu tersisa atau tak seluruhnya terpakai pada satu tahun anggaran. Istilahnya, utang mubazir yang saldonya tiap tahun justru bertambah. Utang yang tak terpakai itu pun ditambah lagi dengan anggaran lainnya yang tak terserap optimal setiap tahunnya dan bertumpuk menjadi Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAL sendiri adalah saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
Pendeknya, SAL adalah sisa uang dikantong kita di akhir tahun yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran selama bertahun-tahun, di dalamnya termasuk perolehan pendapatan dan utang.
Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang terbit Mei 2017 kemarin, SAL awal 1 Januari 2016 sebesar Rp 107,91 triliun dengan penyesuaian SAL Awal Rp 0,35 triliun. Kemudian penggunaan SAL pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 19,01 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai 31 Desember 2016 sebesar Rp 26,16 triliun dan Penyesuaian SAL sebesar minus Rp 2,22 triliun. Dengan begitu, Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2016 adalah sebesar Rp 113,19 triliun
Jumlah SAL pemerintah pusat sendiri belakangan terus naik. Jika pada 2015 lalu sebesar Rp 86 triliun kemudian menjadi hampir Rp 108 triliun atau naik sebesar Rp 22 triliun di 2016. Sayangnya, besaran SAL yang bertambah juga selalu dikontribusi dari adanya SiLPA.
SiLPA sendiri sejatinya menggambarkan pembiayaan atau utang yang tidak digunakan dalam APBN tahun sebelumnya. Padahal, beban bunga dari utang tersebut tetap berjalan. Pada APBN 2017 bunga utang yang ditanggung pemerintah saja mencapai Rp 221 triliun, angka ini meningkat 21 persen dari pembayaran bunga utang pada APBN-P 2016 sebesar Rp 182 triliun. Selama lima tahun terakhir rata-rata peningkatan pembayaran bunga utang mencapai 17persen.
Analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Dani Setiawan kepada Validnews, menuturkan posisi Rupiah yang rendah belakangan bahkan makin mendongkrak pembayaran bunga utang dan pokok utang pemerintah. Ironisnya, sejak tiga tahun terakhir untuk membayar cicilan dan bunga utang yang telah jatuh tempo, "Pemerintah harus menarik utang baru. Gali lubang tutup lubang,” serunya.
Sebenarnya, dengan masih adanya uang di kantong, pemerintah bisa mengunakan SAL untuk memenuhi kebutuhan arus kas (cashflow) di awal tahun seperti untuk membayar gaji pegawai, sementara penerimaan pajak belum terkumpul. SAL juga tentu bisa menjadi mengurangi rencana penarikan utang baru, apalagi untuk menutup utang lama.
Namun, mulai awal Desember tahun lalu saja sudah dinerbitkan surat utang berdenominasi dollar Amerika Serikat atau global bond sebesar US$ 3,5 miliar. Alasan penerbitan tersebut untuk menutupi kebutuhan belanja pada awal tahun 2017 (prefunding) yang masuk dalam realisasi pembiayaan semester pertama 2017.
Akhir Maret 2017, pemerintah pun kembali menerbitkan sukuk global di pasar internasional sebesar US$ 3 miliar atau setara Rp 40 triliun, yang terdiri dari US$ 1 miliar untuk tenor 5 tahun dan US$ 2 miliar untuk tenor 10 tahun.
Padahal, Kementerian Keuangan sendiri pernah mengungkapkan, kebutuhan anggaran pada awal 2017 guna membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah hanya mencapai sekitar Rp 50 triliun. Artinya bisa diambil sepenuhnya dari SAL.
Tampaknya pemerintah harus mengingat lagi, utang memang bisa membantu, tapi bisa juga menjadi hantu di masa depan. Terlebih lagi, utang yang terus membesar tak banyak dirasakan rakyat bawah. United Nations Development Programme/UNDP) dalam laporan Human Development Report 2016 misalnya mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, turun dari posisi 110 di 2014.
Kualitas manusia Indonesia kalah dari Malaysia, bahkan juga lebih rendah dari Turki. IPM Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, dengan skor 0,689. Sedangkan Malaysia ada di peringkat 59 dengan skor 0,789, dan Turki di peringkat 71 dengan skor 0,767.
UNDP pun melansir, ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp 20 ribu per hari dan sekitar 19,4 juta orang menderita gizi buruk. Untuk tingkat kesehatan dan kematian, sekitar dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap.
Kemudian, angka kematian ibu masih sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara untuk akses ke layanan dasar, UNDP mencatat hampir lima juta anak tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkat putus sekolah yang tinggi.
Data terakhir BPS pun menyebutkan, sampai Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah sebanyak 6,90 ribu orang menjadi 27,77 juta orang atau 10,64%. Pada September 2016 penduduk miskin tercatat sebesar 27,76 juta orang atau 10,70%.
Utang memang tak haram, tapi harus bermanfaat. Apakah utang memang jalan satu-satunya untuk berkembang dan membawa masa depan lebih cepat? Jangan sampai tagline “Bring Tomorrrow Today” yang diusung suatu lembaga pembiayaan nasional, justru merampas masa depan anak cucu kita, hanya karena kita sudah menggunakannya dengan serakah saat ini.
Atau, mungkin pemerintah sangat yakin, anak cucu kita nanti pasti bisa melunasi dosa leluhurnya saat ini? (Uji Coba saja)
Jakarta Indonesia-Rasio utang Indonesia terhadap Gross Domestic Product (GDP) saat ini mencapai 27 persen (GDP sekitar Rp 13.000 triliun). Dengan rasio tersebut, setiap penduduk Indonesia memiliki tanggungan utang negara sebesar US$ 997 atau setara Rp 13 juta perkepala.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati jika dihitung dari hampir 260 juta penduduk, diperkirakan perkepala dari kita semua memiliki utang masing-masing US$ 997. Diakuinya angka tersebut masih cuku tinggi, tapi tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara lain.
Mantan Direktur pelaksana World Bank ini membandingkan rasio utang negara lain yang masih jauh lebih besar dibandingan Indonesia. Dikatakannya, Di Amerika Serikat, setiap kepala menanggung utang US$ 62.000. Sedangkan di Jepang bahkan mencapai sebesar US$ 85.000.
"Saat ini rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih berada di bawah 30% dan defisit APBN pada kisaran 2,5%. Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan negara G-20 lainnya," jelas Sri Mulyani seperti dikutip dari akun Facebook-nya, Jumat (7/7).
Ia memastikan, Indonesia tetap mengelola utang secara prudent (hati-hati). Presiden Joko Widodo tengah menggelontorkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur di Indonesia. “Ini merupakan upaya pemerintah mengejar ketinggalan pembangunan," lanjutnya.
Pemerintah sejauh ini memang menilai utang menjadi sesuatu yang tak bisa terelakan mengingat Indonesia masih mengalami defisit anggaran beberapa tahun terakhir. Misalnya saja, penerimaan dalam APBN P 2016 diproyeksikan sebesar Rp 1.786,2 triliun dengan belanja negara Rp 2.082,9 triliun.
Namun, penerimaan hanya terealisasi Rp 1.551,8 triliun (86,9 persen dari target) dengan realisasi belanja negara Rp 1.859,5 triliun (89,3 persen dari target). Defisit anggaran pun tercatat Rp 307,7 triliun atau 2,46 persen terhadap PDB.
Di dalam APBN 2017 penerimaan negara di proyeksikan sebesar Rp 1.750,3 triliun, dengan rencana belanja sebesar Rp 2.080,5 triliun. Defisit anggaran pun dipasang di angka 2,41 persen terhadap PDB atau Rp 330,2 triliun.
Angka-angka ini kembali diubah lewat APBN Perubahan 2017 mengingat ada asumsi target penerimaan pajak masih akan mengalami shortfall tahun ini. Artinya, utang bakal menjadi jalan cepat buat pemerintah untuk menambal kurangnya penerimaan negara.
Dalam rancangan APBN-P 2017, shorfall penerimaan perpajakan ditaksir mencapai sekitar Rp 48 triliun. Konsekuensinya, target perpajakan pun direvisi turun dari Rp 1.499 triliun menjadi Rp 1.451 triliun. Sayangnya, shortfall pajak justru tidak diikuti oleh pemangkasan belanja, seperti yang dilakukan pada tahun 2016 lalu. Alasan pemerintah, saat ini tengah butuh biaya besar untuk mengenjot infrastruktur.
Pada APBN-P 2017, pagu belanja negara justru dinaikkan dari Rp 2.080,5 triliun menjadi Rp 2.111,4 triliun. Alhasil, defisit anggaran akan naik dari Rp 330,2 triliun menjadi Rp 397 triliun. Ujungnya defisit membengkak dari 2,41% menjadi 2,92 terhadap PDB, hampir menyentuh batas atas defisit anggaran 3 persen dari PDB sesuai UU Keuangan Negara.
Dengan kenaikan defisit tersebut, total utang pemerintah yang akan ditarik meningkat dari Rp 384,69 triliun menjadi Rp 426,99 triliun. Jika anggaran utang tersebut terealisasi, maka pada akhir 2017, outstanding utang pemerintah akan mencapai Rp 3.962,86 triliun.
Sebuah ‘percepatan’ pertumbuhan utang yang signifikan. Bisa dilihat total utang baru selama 2,5 tahun terakhir sudah mencapai Rp 1.210,92 triliun. Sebagai perbandingan, dalam tiga tahun terakhir pemerintahan sebelumnya (SBY), tambahan utang baru ‘hanya’ mencapai Rp 619,74 triliun.
Bahkan, pertumbuhan utang dalam 2,5 tahun pemerintahan Joko Widodo saat ini, masih lebih besar dibandingkan penambahan utang pada periode kedua pemerintahan Presiden SBY secara keseluruhan lima tahun (2009-2014) yang sebesar Rp1.019 triliun. Sampai akhir tahun ini, hampir dipastikan utang pemerintahan Joko Widodo pun akan bertambah dan melampaui level Rp 1.500-an triliun dalam tiga tahun pertamanya. .
Defisit Keseimbangan Primer
Pertanyaannya, apa yang menjadi parameter negara harus belanja lebih besar di banding pendapatannya yang diproyeksikan selama setahun ke depan? Mengapa setiap tahun belanja negara harus meningkat, sementara pertumbuhan pendapatan terus tak bisa mengejar pertumbuhan kebutuhan belanja?
Jika besaran belanja negara ini tahun depan sama seperti tahun ini, apakah harus dianggap negara tak berkembang? Faktanya, untuk memenuhi hasrat belanja negara, utang yang ditarik pemerintah lewat sejumlah instrumen dan kreditur jumlahnya sudah sangat besar dan makin sulit dikurangi.
Data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan menyebutkan, dalam lima tahun terakhir, saldo utang pemerintah selalu meningkat. Jika di tahun 2012, posisi utang pemerintah sebesar Rp 1.977,77 triliun, di tahun 2016 menjadi sebesar Rp 3.511,16 triliun.
Hingga Mei 2017 posisi utang pemerintah pusat mencapai Rp 3,672,43 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari surat berharga negara (SBN) sebesar Rp2,943,72 triliun atau 80,16 persen dari total utang. Sementara sisanya, Rp 728,7 triliun merupakan pinjaman.
Sejak awal penyusunan anggaran di tahun sebelumnya, pemerintah memang sudah menetapkan kekurangan (defisit) bakal ditutup oleh utang. Rencana penarikan utang pun sudah disusun sesitematis mungkin dengan jadwal yang terencana.
Bahkan strategi berutang pun disusun hingga ada istilah Front Loading Strategy atau menarik utang di awal periode tahun berjalan. “Selama anggaran direncanakan selalu defisit, maka pasti ada penambahan utang,” kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.
Menurut mantan Menteri Keuangan ini, utang menjadi kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang masih melambat. Dijelaskannya, dari sisi konsumsi rumah tangga dan investasi swasta cenderung melambat, sehingga diperlukan dorongan belanja pemerintah yang lebih ekspansif.
Defisit budget sejatinya diterapkan untuk mengganti skema budget berimbang (pengeluaran tak boleh lebih dari pendapatan) yang sebelumnya digunakan dalam APBN pemerintahan Orde Baru. Namun, kini skema ini diubah, APBN boleh defisit asalkan dalam batas yang wajar. Sehingga ditetapkan batas maksimal defisitnya sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Mantan Wakil Presiden Boediono, sebetulnya memang tidak ada penjelasan ilmiah mengenai batasan tersebut hal itu. "Saya membuat kebijakan itu hanya menyontek dari Eropa," ujar Menteri Keuangan periode 2001-2004 tersebut dalam sebuah diskusi di Kementerian Keuangan beberapa tahun lalu.
Kala itu, cara tersebut dinilai jitu untuk menjawab masalah saat itu; utang membengkak, penerimaan minim, sementara itu Indonesia butuh tenaga untuk menggenjot perekonomian yang saat itu masih minus 13 persen. Hanya saja, ternyata skema defisit budget tersebut masih terus dilakukan sampai saat ini.
Ekonom INDEF Enny Sri Hartati kepada Validnews mengatakan, ketika defisit APBN melebar itu artinya pemerintah butuh uang yang biasanya diambil lewat jalan utang. Menurutnya, utang memang bukanlah barang haram, hanya saja harus dilihat lagi seberapa efektif utang tersebut digunakan untuk memacu penerimaan pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.
“Masalahnya, utang ini punya garansi nggak untuk meningkatkan penerimaan pemerintah ke depan? Ini ditunjukkan dari neraca keseimbangan primer,” kata Enny.
Sayangnya, sejak 2012 terjadi defisit keseimbangan primer hingga tahun depan terus bertambah. Ini menunjukkan belanja APBN tidak efektif. “Jadi kita ambil utang, tapi beban kita bertambah, malah menambah defisit. Buat apa kita ambil utang kalau akhirnya hanya untuk menutup utang lama, bukan untuk kegiatan produktif,” lanjutnya.
Sekadar mengingatkan, Neraca Keseimbangan Primer adalah realisasi pendapatan negara dikurangi dengan realisasi belanja negara, di luar pembayaran utang. Defisit keseimbangan primer menunjukkan adanya utang yang digunakan untuk membayar utang yang jatuh tempo pada tahun tersebut, ibaratnya gali lubang tutup lubang.
Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Keuangan terlihat pada 2011, nilai keseimbangan primer pada APBN masih positif sebesar Rp 8,9 triliun (realisasi). Kemudian berubah negatif menjadi Rp -52,8 triliun (2012), Rp -98,6 triliun (2013), Rp -93,3 triliun (2014), Rp -142,5 triliun (2015), Rp-125,6 (2016), Rp -109 Triliun (APBN 2017) dan Rp 178 triliun (APBN Perubahan 2017).
Dengan keseimbangan primer yang terus negatif tersebut, dapat dikatakan kemampuan APBN kita untuk mengurangi beban utangnya masih lemah. Kondisi ini perlu segera diperbaiki agar tidak membahayakan kesehatan fiskal,
Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri sempat mengakui, postur APBN belakangan ini memang tidak sehat. Karenanya, pengelolaan APBN harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menjadi momok bagi APBN itu sendiri.
"Kalau ingin belanja lebih banyak, harus mendapatkan pajak yang lebih banyak. Dengan demikian seluruh kebutuhan bisa didapat dan tidak membahayakan ekonomi," kata Sri Mulyani dikutip dari Antara (12/7).
Mengenai penetapan target APBN, khususnya anggaran belanja, Sri bahkan menilainya sebagai sesuatu yang cukup lucu. Jika pada satu sisi, pemerintah harus menetapkan anggaran belanja yang pasti akan digunakan, di sisi lain pemerintah harus menetapkan penerimaan yang tak pasti akan diperoleh.
Ironisnya, utang yang sudah disiplin ditarik sesuai jadwalnya, selalu tersisa atau tak seluruhnya terpakai pada satu tahun anggaran. Istilahnya, utang mubazir yang saldonya tiap tahun justru bertambah. Utang yang tak terpakai itu pun ditambah lagi dengan anggaran lainnya yang tak terserap optimal setiap tahunnya dan bertumpuk menjadi Saldo Anggaran Lebih (SAL).
Menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, SAL sendiri adalah saldo yang berasal dari akumulasi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
Pendeknya, SAL adalah sisa uang dikantong kita di akhir tahun yang berasal dari penerimaan dan pengeluaran selama bertahun-tahun, di dalamnya termasuk perolehan pendapatan dan utang.
Dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang terbit Mei 2017 kemarin, SAL awal 1 Januari 2016 sebesar Rp 107,91 triliun dengan penyesuaian SAL Awal Rp 0,35 triliun. Kemudian penggunaan SAL pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp 19,01 triliun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai 31 Desember 2016 sebesar Rp 26,16 triliun dan Penyesuaian SAL sebesar minus Rp 2,22 triliun. Dengan begitu, Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2016 adalah sebesar Rp 113,19 triliun
Jumlah SAL pemerintah pusat sendiri belakangan terus naik. Jika pada 2015 lalu sebesar Rp 86 triliun kemudian menjadi hampir Rp 108 triliun atau naik sebesar Rp 22 triliun di 2016. Sayangnya, besaran SAL yang bertambah juga selalu dikontribusi dari adanya SiLPA.
SiLPA sendiri sejatinya menggambarkan pembiayaan atau utang yang tidak digunakan dalam APBN tahun sebelumnya. Padahal, beban bunga dari utang tersebut tetap berjalan. Pada APBN 2017 bunga utang yang ditanggung pemerintah saja mencapai Rp 221 triliun, angka ini meningkat 21 persen dari pembayaran bunga utang pada APBN-P 2016 sebesar Rp 182 triliun. Selama lima tahun terakhir rata-rata peningkatan pembayaran bunga utang mencapai 17persen.
Analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Dani Setiawan kepada Validnews, menuturkan posisi Rupiah yang rendah belakangan bahkan makin mendongkrak pembayaran bunga utang dan pokok utang pemerintah. Ironisnya, sejak tiga tahun terakhir untuk membayar cicilan dan bunga utang yang telah jatuh tempo, "Pemerintah harus menarik utang baru. Gali lubang tutup lubang,” serunya.
Sebenarnya, dengan masih adanya uang di kantong, pemerintah bisa mengunakan SAL untuk memenuhi kebutuhan arus kas (cashflow) di awal tahun seperti untuk membayar gaji pegawai, sementara penerimaan pajak belum terkumpul. SAL juga tentu bisa menjadi mengurangi rencana penarikan utang baru, apalagi untuk menutup utang lama.
Namun, mulai awal Desember tahun lalu saja sudah dinerbitkan surat utang berdenominasi dollar Amerika Serikat atau global bond sebesar US$ 3,5 miliar. Alasan penerbitan tersebut untuk menutupi kebutuhan belanja pada awal tahun 2017 (prefunding) yang masuk dalam realisasi pembiayaan semester pertama 2017.
Akhir Maret 2017, pemerintah pun kembali menerbitkan sukuk global di pasar internasional sebesar US$ 3 miliar atau setara Rp 40 triliun, yang terdiri dari US$ 1 miliar untuk tenor 5 tahun dan US$ 2 miliar untuk tenor 10 tahun.
Padahal, Kementerian Keuangan sendiri pernah mengungkapkan, kebutuhan anggaran pada awal 2017 guna membayar gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) ke daerah hanya mencapai sekitar Rp 50 triliun. Artinya bisa diambil sepenuhnya dari SAL.
Tampaknya pemerintah harus mengingat lagi, utang memang bisa membantu, tapi bisa juga menjadi hantu di masa depan. Terlebih lagi, utang yang terus membesar tak banyak dirasakan rakyat bawah. United Nations Development Programme/UNDP) dalam laporan Human Development Report 2016 misalnya mencatat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, turun dari posisi 110 di 2014.
Kualitas manusia Indonesia kalah dari Malaysia, bahkan juga lebih rendah dari Turki. IPM Indonesia pada 2015 berada di peringkat 113, dengan skor 0,689. Sedangkan Malaysia ada di peringkat 59 dengan skor 0,789, dan Turki di peringkat 71 dengan skor 0,767.
UNDP pun melansir, ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp 20 ribu per hari dan sekitar 19,4 juta orang menderita gizi buruk. Untuk tingkat kesehatan dan kematian, sekitar dua juta anak di bawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap.
Kemudian, angka kematian ibu masih sebanyak 305 kematian per 100 ribu kelahiran hidup. Sementara untuk akses ke layanan dasar, UNDP mencatat hampir lima juta anak tidak bersekolah dan anak-anak di Papua memiliki tingkat putus sekolah yang tinggi.
Data terakhir BPS pun menyebutkan, sampai Maret 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia bertambah sebanyak 6,90 ribu orang menjadi 27,77 juta orang atau 10,64%. Pada September 2016 penduduk miskin tercatat sebesar 27,76 juta orang atau 10,70%.
Utang memang tak haram, tapi harus bermanfaat. Apakah utang memang jalan satu-satunya untuk berkembang dan membawa masa depan lebih cepat? Jangan sampai tagline “Bring Tomorrrow Today” yang diusung suatu lembaga pembiayaan nasional, justru merampas masa depan anak cucu kita, hanya karena kita sudah menggunakannya dengan serakah saat ini.
Atau, mungkin pemerintah sangat yakin, anak cucu kita nanti pasti bisa melunasi dosa leluhurnya saat ini? (Uji Coba saja)
The latest Employment Situation report from the Bureau of Labor Statistics shows weekly employee earnings have grown $75 since tax reform passed, well short of the $4,000 to $9,000 annual increases projected by President Trump Donald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE and House Speaker Paul Ryan
Donald John TrumpRobert De Niro, Ben Stiller play Mueller and Cohen in 'SNL' parody of 'Meet the Parents' Trump order targets wide swath of public assistance programs Comey says Trump reacted to news of Russian meddling by asking if it changed election results MORE and House Speaker Paul Ryan Paul Davis RyanTrump order targets wide swath of public assistance programs Sunday shows preview: White House officials talk Syria strike Wage growth well short of what was promised from tax reform MORE (R-Wis.).
Paul Davis RyanTrump order targets wide swath of public assistance programs Sunday shows preview: White House officials talk Syria strike Wage growth well short of what was promised from tax reform MORE (R-Wis.).
During the three months following passage of the tax bill, the average American saw a $6.21 increase in average weekly earnings. Assuming 12 weeks of work during the three months following passage of the corporate tax cuts, this equates to a $75 increase.
Assuming a full 52 weeks of work, the $6.21 increase in weekly earnings would result in a $323 annual increase, nowhere near the minimum $4,000 promised and $9,000 potential annual increases projected by President Trump and Speaker Ryan if significant cuts were made to corporate tax rates.
Unless something drastically changes, it seems that Americans are going to have to settle for much less than the $4,000 to $9,000 projected wage increases. An extra $322 a year isn’t going to do much to pay down the $1 trillion in additional debt they are projected to take on as a result of the tax cuts.
Yet, a key part of the argument for the recently passed corporate tax cuts and more than a trillion dollars in debt was the substantial wage hike promised by the president’s Council of Economic Advisers (CEA).
From a document titled, “Corporate Tax Reform and Wages: Theory and Evidence,” on the White House’s website:
“Reducing the statutory federal corporate tax rate from 35 to 20 percent would, the analysis below suggests, increase average household income in the United States by, very conservatively, $4,000 annually.”
The document goes on to say:
“When we use the more optimistic estimates from the literature, wage boosts are over $9,000 for the average U.S. household.”
No less than Speaker Ryan’s website trumpeted the Council of Economic Advisers report claiming that on average, the proposed corporate tax cuts would result in at least a $4,000 annual increase in wages.
Now, some supporters of the tax bill may say this analysis is unfair because it is too early for the effects of the tax bill to show up in wages. By that logic, they also shouldn’t take credit for reported employment growth increases.
Still others may point to the $1,000 bonuses announced by some companies shortly after passage of the tax bill. First, that is significantly less than the promised $4,000 to $9,000. Second, these are not wage increases; these are one-time bonuses.
Will companies pay them again, and if so when? Third, the $1,000 represents a fraction of the estimated potential company tax savings.
Using 2016 net income, 2016 effective tax rates, the new 21-percent corporate tax rate and company bonuses, we estimated company bonuses as a percentage of a number of company’s potential tax savings. The results: In many cases, the bonuses represent a mere pittance of the possible tax savings.
Navient announced that it would be giving $1,000 bonuses to 98 percent of its 6,7000 employees, paying out nearly $7 million in bonuses. While that may seem generous, it pales in comparison to Navient’s potential tax savings.
Using Navient’s 2016 net income, its 2016 effective tax rate, estimated annual tax savings of nearly $200 million and its announced bonuses, we calculated that the announced bonuses represent less than 4 percent of Navient’s potential tax savings.
Turning to the airline industry, JetBlue’s employees might be feeling blue if they realized that their $1,000 bonuses are estimated to be less than 10 percent of JetBlue’s potential tax savings, while American Airlines’ bonuses are estimated to represent less than 15 percent of its estimated potential annual tax savings
Not to be outdone, Comcast’s bonuses represent less than 8 percent of its estimated potential annual tax savings, while Walmart appears downright generous, giving an estimated $0.16 of every dollar of its estimated potential annual tax savings to employees in the form of bonuses.

Source: Solutionomics
What happened to the minimum $4,000 promised? I guess like many promises by politicians, they were empty. Instead, they seem to have gone to share buybacks. For the period December 2017 through February 2018, share buybacks more than doubled to $200 million.
Is a $323 wage increase and a one-time bonus of $1,000 that represents a fraction of estimated potential company tax savings worth the more than $1 trillion in additional debt placed on Americans? Is this the best Congress could do? No.
Instead, Congress could have simply made each company’s tax cut contingent on each company increasing wages. The problem is that some companies receiving tax cuts didn’t raise wages.
If Congress had made each company’s tax cut contingent on each company’s wage increases, the American people would have gotten more bang for their tax cut bucks. Additionally, this would have created a real incentive for companies to raise wages: Increase wages, get a tax cut; don’t and you won’t.
If the justification for saddling the American people with at least $1 trillion in additional debt was greater wage growth, tax cuts should have been tied to each company’s wage growth; that’s just logical. That’s getting a better deal for the American people, and that’s getting a better return on investment.
Chris Macke is the founder of Solutionomics, a think tank focused on developing solutions for a more efficient, merit-based corporate tax code. He has advised the U.S. Federal Reserve by providing market updates and implications of monetary policy changes on asset valuations and market distortions, and he's a contributor to the Fed Beige Book. Find him on Twitter: @solutionomics.




























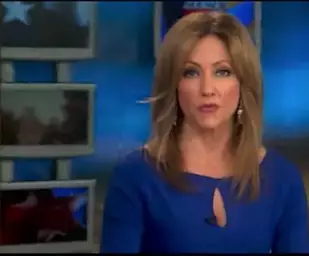





















































































Saya telah berpikir bahwa semua perusahaan pinjaman online curang sampai saya bertemu dengan perusahaan pinjaman Suzan yang meminjamkan uang tanpa membayar lebih dulu.
BalasHapusNama saya Amisha, saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan orang-orang yang mencari pinjaman internet di Asia dan di seluruh dunia untuk berhati-hati, karena mereka menipu dan meminjamkan pinjaman palsu di internet.
Saya ingin membagikan kesaksian saya tentang bagaimana seorang teman membawa saya ke pemberi pinjaman asli, setelah itu saya scammed oleh beberapa kreditor di internet. Saya hampir kehilangan harapan sampai saya bertemu kreditur terpercaya ini bernama perusahaan Suzan investment. Perusahaan suzan meminjamkan pinjaman tanpa jaminan sebesar 600 juta rupiah (Rp600.000.000) dalam waktu kurang dari 48 jam tanpa tekanan.
Saya sangat terkejut dan senang menerima pinjaman saya. Saya berjanji bahwa saya akan berbagi kabar baik sehingga orang bisa mendapatkan pinjaman mudah tanpa stres. Jadi jika Anda memerlukan pinjaman, hubungi mereka melalui email: (Suzaninvestment@gmail.com) Anda tidak akan kecewa mendapatkan pinjaman jika memenuhi persyaratan.
Anda juga bisa menghubungi saya: (Ammisha1213@gmail.com) jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut